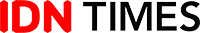Aprila Wayar dan Perjuangannya Menjadi Putri Papua Seutuhnya
 IDN Times/Sukma Shakti
IDN Times/Sukma Shakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Bagi sebagian masyarakat Indonesia di wilayah barat, misalnya di kota-kota besar di Pulau Jawa, Papua terasa sangat jauh. Konsep tentang wilayah, masyarakat serta budayanya pun hanya diperoleh dari buku pelajaran, pemberitaan media, serta pernyataan pemerintah.
Novelis kelahiran Papua, Aprila Wayar, menuangkan kegelisahannya (dan bisa jadi mewakili mayoritas masyarakat Papua) melalui karya literatur terbarunya, "Sentuh Papua". Aprila menceritakan bagaimana kondisi Papua. Sudut pandangnya cukup menarik. Tak sekadar putri Papua, Aprila juga mampu menyajikan pandangan Papua dari penilaian masyarakat luar. Maklum, ia pernah merantau ke Jawa sebelum kembali ke Papua untuk menjadi jurnalis.
Ia tahu rasanya menjadi anak Papua. Ia juga mengerti asumsi masyarakat di luar Papua tentang daerah asalnya. Dalam sesi terakhir perbincangan IDN Times dengan Aprila, ia berharap agar orang-orang Indonesia di luar Papua memahami rasanya menjadi warga asli Bumi Cendrawasih.
Baca juga: Aprila Wayar, Suarakan Jeritan Papua Melalui Novel
1. Prasangka tentang Papua sudah muncul sejak dari bentuk fisik
Perempuan yang sempat mengenyam pendidikan di Wamena, Tasikmalaya, serta Yogyakarta itu menuturkan bahwa ia merasakan diskriminasi sejak kecil. Sebagai murid kelas tiga SD di Tasikmalaya yang baru pindah dari Papua, Aprila mengaku soal fisik pun bisa menjadi masalah.
"Teman-teman saya selalu menganggap remeh. Itu anak Papua, kulit hitam, keriting. Saya sekolah di sekolah China bonafide di Tasikmalaya. Kemudian, ketika saya mulai sekolah pertama, saya ranking 27 dari 30 siswa. Saya pulang, saya nangis, saya bilang 'Ma, saya mau pulang ke Wamena'. Mama bilang,'Kenapa?'. Saya jawab,'Di Wamena saya ranking satu. Di sini saya ranking 27.'"
Setelah mamanya memanggil guru les Matematika, nilai Aprila pun perlahan tapi pasti mulai membaik. Rasa percaya dirinya juga meningkat. Teman-teman yang dulu meledeknya justru meminjam pekerjaan rumahnya.
"Saya yang kulitnya tidak terlalu hitam seperti orang Papua lain, saya didiskriminasi seperti ini. Saya membayangkan saudara-saudara saya yang lain yang benar-benar hitam dan benar-benar keriting. Apa yang terjadi pada mereka?" tanya Aprila.
"Makanya kalau ada anak Papua yang kuliah di Jawa atau di luar negeri, sukses, pulang dengan gelar master apa segala macam, saya ngacungin jempolnya empat. Kenapa? Mereka bukan cuma berhasil di pendidikan, mereka berhasil dalam hal adaptasi. Itu mereka menghadapi dua masalah."
2. Ada perasaan asing yang muncul akibat mendengarkan prasangka tersebut
Tak mudah untuk menghadapi prasangka bahwa anak Papua selalu tertinggal, misalnya dalam hal akademik. Apalagi ketika penampilan fisiknya sudah dianggap berbeda. Suka atau tidak, tertanam pada benak Aprila, dan barangkali anak-anak Papua lainnya, bahwa mereka asing.
"Ketika saya duduk di samping orang Indonesia, lalu dia bertanya 'Oh, orang Papua, ya?' kayak pertanyaan yang membuat saya [berpikir bahwa] saya ini memang bukan Indonesia. Ada perasaan seperti itu." Namun, pertanyaan tentang identitas juga tak mudah untuk dijawab olehnya.
Editor’s picks
"Di sisi lain, saya dilematis ketika saya bilang saya orang Papua, saya tidak bisa berbahasa ayah-ibu saya. Nah, terus, saya harus bilang saya orang apa? Banyak anak-anak generasi muda yang kemudian sama seperti saya, tercabut dari akar.
Kenapa? Ada sejarah yang membuat kami tidak bisa berbahasa: sejarah kekerasan. Ini mengakibatkan kami tidak bisa berbahasa ayah dan ibu kami. Kami dipaksa menggunakan bahasa Indonesia. Orangtua saya dipaksa menggunakan bahasa Indonesia."
3. Aprila menganalogikan Papua sebagai "anak adopsi" Indonesia
Segala pengalaman pribadinya dan apa yang ia saksikan sebagai jurnalis di Papua membuatnya mengibaratkan Papua bukan sebagai anak kandung Indonesia. Ia mencontohkan saat penelitian di Tolikara pada 2011 dan menemukan anggota keluarga penduduk di sana yang sakit keras, tapi tak bisa berobat.
"Saya tanya 'Terus kalau sehari-hari sakit begini, Mama bagaimana berobat?'. Mereka bilang 'Aduh! Ini anak kalau turun ke Puskesmas, jauh. Dan kita tidak punya uang untuk naik ojek. Ojek sekali jalan Rp 30 ribu-Rp 50 ribu dari atas. Ya, kami tidak bisa bikin apa-apa'," ucap Aprila sambil menirukan si mama tersebut.
"Saya katakan 'Kalau saya kasih uang untuk berobat, Mama mau turun tidak?'. Dia bilang,'Tidak'. Lalu, saya bingung. Dia jawab 'Itu yang jaga di Puskesmas semua tentara'. Baru saya ngeh di situ trauma-trauma kekerasan militer itu terasa sekali di masyarakat. Dan akses-askes kesehatan dan lain-lain semua di banyak titik itu masih menjadi otoritasnya keamanan juga. Dan mereka akhirnya menerima keadaan sakit sampai mati di tempat tidur."
"Orang dari wilayah barat Indonesia selalu menghakimi kami ingin memerdekakan diri, kami tidak mampu, kami tidak ini, kami tidak itu. Tapi [mereka] tidak melihat hal yang sebenarnya. Apa yang sih yang terjadi di sana [Papua]? Ini lho perasaan-perasaan kami," tambahnya.
"Ketika kami tinggal di tanah kami, kami diintimidasi. Ketika kami ke Jawa, kami didiskriminasi. Ketika kami ke luar negeri, orang luar negeri bilang 'Kami tidak tahu Papua di mana'. Jadi, kami seperti orang yang kemudian hidup di negeri antah berantah. Kami rindu tanah kami, kami mau pulang, kami dibunuh."
Ia pun menuturkan kepada IDN Times tentang analogi yang ia sempat bawakan ketika diundang hadir dalam acara Ubud Writers Festival pada 2012 lalu:
"Indonesia itu sebuah keluarga yang sudah menikah tahun ’45. Kemudian, keluarga ini punya banyak anak. Nah, di tahun ’69, keluarga Melayu ini kemudian mengadopsi seorang anak laki-laki berkulit hitam yang setelah dia mulai bisa makan dan duduk, dia setiap kali makan itu si anak laki-laki ini dia tidak duduk di meja makan tapi di lantai dan diberi menu makanan yang berbeda setiap kali makan.
Keluarga ini duduk bersama anak-anaknya di meja makan dan ini berlangsung selama puluhan tahun sampai si anak laki-laki berkulit hitam ini sudah dewasa. Ketika sudah dewasa dia lihat 'Oh, ternyata secara fisik saya berbeda dengan keluarga ini'. Dia tahu bahwa dia anak adopsi.
Pertanyaannya kan apakah si orang tua angkat ini mau mengajak dia duduk bersama-sama dan makan dengan menu makanan yang sama? Kemudian tanya sama dia 'Apa yang kamu mau?' atau dia sendiri akan berusaha lari dari rumah itu karena tiap hari mendapatkan siksaan dari keluarganya. Tapi dia bukan anak kecil, dia sudah dewasa."
"Kira-kira itu perasaan kami orang Papua."
Baca Juga: Novelis Aprila Wayar Bicara Soal Transmigrasi dan Konflik di Papua